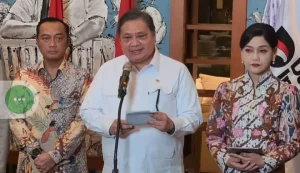Siaran Asing Ditutup, Warga Korea Utara Terputus dari Dunia

JAKARTA — Langkah Amerika Serikat dan Korea Selatan menghentikan siaran radio lintas batas menandai babak baru isolasi informasi bagi masyarakat Korea Utara. Keputusan itu membuat jutaan warga di negara tertutup tersebut semakin kehilangan akses terhadap informasi independen dari luar negeri.
“Ini sangat buruk bagi rakyat Korea Utara dan jadi kemunduran yang sangat serius untuk hak asasi manusia di sana,” ujar Kim Eu-jin, seorang pembelot yang melarikan diri dari Korea Utara bersama ibu dan saudarinya pada tahun 1990-an.
Ia menilai keputusan dua negara itu justru memperkuat dominasi propaganda rezim Pyongyang. “Pemerintah menolak telak kebebasan rakyat Korea Utara untuk mengakses informasi, dan sekarang yang akan mereka dengar hanyalah propaganda Pyongyang,” katanya kepada DW.
Sebelumnya, warga Korea Utara diam-diam mengandalkan Radio Free Asia (RFA) dan Voice of America (VOA) yang disiarkan dari Amerika Serikat, serta Voice of Freedom dari Korea Selatan, untuk memperoleh berita yang berbeda dari versi pemerintah mereka. Meski berisiko tinggi, mendengarkan siaran asing menjadi satu-satunya cara bagi sebagian warga untuk mengetahui kondisi luar negeri.
Kim mengungkapkan bahwa rezim Pyongyang selama ini menindak keras siapa pun yang kedapatan mendengarkan radio asing. Mereka yang tertangkap kerap diadili secara terbuka dan dijatuhi hukuman berat, mulai dari kerja paksa hingga hukuman mati dalam kasus ekstrem.
Menurutnya, pemerintah Korea Utara semakin agresif memperingatkan rakyatnya agar tidak mengakses media asing. Ketakutan rezim terhadap kebocoran informasi membuat kontrol terhadap warganya semakin ketat.
Keputusan penghentian siaran ini bermula dari kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kembali menjabat pada awal tahun. Ia mengeluarkan perintah eksekutif untuk membubarkan lembaga induk VOA, yakni US Agency for Global Media, sehingga ratusan pegawai kehilangan pekerjaan.
Tidak lama kemudian, Korea Selatan mengikuti langkah serupa. Pada akhir Agustus, Seoul mengumumkan penghentian siaran Voice of Freedom yang telah mengudara selama 15 tahun, serta membongkar sistem pengeras suara di perbatasan yang selama ini menyiarkan musik dan berita ke wilayah Utara.
Pemerintah Korea Selatan berdalih, keputusan tersebut diambil demi menurunkan ketegangan dengan Pyongyang dan membuka peluang dialog baru. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda positif dari Korea Utara untuk merespons inisiatif itu.
Pemimpin redaksi Radio Free Asia, Rosa Hwang, menyebut penutupan siaran mereka sebagai pukulan besar terhadap kebebasan pers. “Redaksi gelap. Mikrofon dimatikan. Siaran dibungkam,” ujarnya, menegaskan bahwa 26 juta warga Korea Utara kini benar-benar kehilangan jendela informasi dari dunia luar.
Sebuah analisis yang dirilis situs 38 North pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa siaran radio anti-rezim menurun hingga 85 persen sejak kebijakan penghentian tersebut, sementara program televisi lintas batas hampir lenyap sama sekali.
Para ahli menilai, Pyongyang semakin mahir mengacaukan sinyal siaran asing dan memperketat pengawasan dengan Undang-Undang Anti-Pemikiran dan Budaya Reaksioner sejak 2020. Pandemi COVID-19 pun memperburuk situasi, karena jalur penyelundupan USB dan kartu memori dari luar menjadi tertutup.
Lim Eun-jung, profesor studi internasional di Kongju National University, mengatakan, “Saya yakin pemerintah Pyongyang sangat senang dengan perkembangan ini.” Ia menilai langkah Korea Selatan dan AS justru membuat warga Korea Utara semakin bergantung pada media resmi rezim.
Pembelot Kim Eu-jin menambahkan, “Siaran itu mengajarkan orang di Korea Utara tentang hak asasi manusia. Itu memberi tahu mereka apa itu kebebasan.” Ia menyesalkan, penghentian siaran tersebut seolah membuat dunia luar “menjadi perpanjangan tangan” rezim yang selama ini menindas rakyatnya. []
Siti Sholehah.